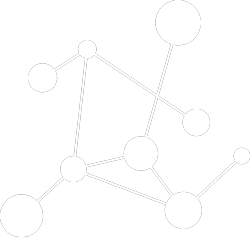Beberapa waktu yang lalu, sebuah kompetisi seni kontemporer bertajuk Asia Art Award (A3) diselenggarakan di kota Seoul, Korea Selatan. Perhelatan ini diselenggarakan oleh CJ Culture Foundation, Alternative Space LOOP, dan Korea Sports Promotion Foundation yang juga didukung oleh beberapa institusi budaya yang berasal dari beberapa negara Eropa dan Asia Pasifik. Sejak tanggal 9 April s/d 6 Juni 2010, kompetisi ini menampilkan karya dari 6 finalis yang dipamerkan di Soma Museum of Art yang terletak di kompleks Olimpiade Seoul. Mereka terdiri dari Apichatpong Weerasethakul (TH), Ashok Sukumaran (IN), ChimPom (JP), Jompet Kuswidananto (ID), Shi Jin Song (CN) dan Yangachi (KR). Tampil sebagai pemenang pertama yang berhak mendapatkan hadiah sebesar USD. 20.000,- adalah Apichatpong Weerasethakul yang menampilkan karya video dengan judul “Phantoms of Nabua” (2009).
Kompetisi ini digadang-gadang sebagai babak baru perkembangan seni kontemporer di wilayah Asia. Suh Jinsuk, kurator dari Alternative Space LOOP yang bertindak sebagai direktur kompetisi ini menuliskan bahwa A3 merupakan titik balik bagi perkembangan seni rupa di Asia yang sebelumnya selalu mengekor perkembangan seni kontemporer barat. Tidak tanggung-tanggung, untuk menyelenggarakan kompetisi ini panitia melibatkan sekitar 42 ahli dari Korea Selatan, Jepang, Cina, India dan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk kurator Agung Hujatnikajennong yang mewakili Indonesia. Mereka secara khusus diundang untuk merekomendasikan sekitar 42 seniman yang kemudian diseleksi oleh 7 orang juri utama yang diminta untuk mengusulkan 6 finalis. Adapun dewan juri yang dilibatkan dalam kompetisi ini adalah Alexandra Munroe (US), Apinan Poshyananda (TH), Carolyn Christov-Bakargiev (US), Fumio Nanjo (JP), Jonathan Watkins (UK), Kim Honghee (KR) dan Wu Hung (CN).
Realitas Asia
Dapat dikatakan bahwa karya para seniman yang tampil di dalam kompetisi ini merefleksikan berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan masyarakat di wilayah Asia yang tengah berada di dalam gejolak arus perubahan yang sedemikian pesat. Proses globalisasi yang dirajut kapitalisme global dan teknologi media tampaknya telah menjadi semacam katalis yang melahirkan berbagai kecenderungan baru dalam perkembangan seni kontemporer Asia. Dalam kesempatan ini, masing-masing seniman secara kuat merefleksikan kondisi di sekitar mereka dengan menguak berbagai lapisan sejarah dan narasi lokal yang merekam realitas sosial serta berbagai bentuk ketegangan politik yang disampaikan melalui bahasa visual yang sedemikian beragam. Selain karya video dan instalasi, dalam pameran kita juga dapat menyaksikan karya gambar, fotografi, video, cetak digital, obyek, instalasi dan beragam komposisi bebunyian.
Keragaman bahasa estetik ini misalkan tercermin melalui karya Jompet Kuswidananto yang menampilkan karya instalasi berjudul Java’s Machine: Phantasmagoria (2008). Karyanya sepintas mirip seperti barisan tentara kerajaan yang tegak berdiri dengan karakter yang begitu anggun. Untuk karya ini, Jompet memanfaatkan pelbagai obyek keseharian, cuplikan video dan instrumen robotik yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bebunyian yang mirip seperti arak-arakan kelompok pemain drum band dalam gerak lambat. Secara simbolik karya ini merefleksikan berbagai lapisan narasi sejarah kolonial/ paska-kolonial yang telah menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat Jawa. Selain itu, karya ini juga tampaknya menyiratkan pola relasi antara mesin dan manusia yang terlihat begitu unik.
Pada kesempatan yang sama, kelompok ChimPom menampilkan beberapa karya yang mewartakan lapisan imajinasi kolektif masyarakat Jepang yang disampaikan dengan cara yang sangat lugas dan berani. Karya mereka yang berjudul “Lighting up the sky over Hiroshima” (2009) menjadi bahan perdebatan khalayak luas di Jepang ketika mereka membuat sebuah teks asap raksasa bertuliskan “PIKA” tepat diatas kubah gedung A-Bomb Dome dengan latar belakang langit Hiroshima yang berwarna biru pada tanggal 21 Oktober 2008. Bagi mereka yang mengalami tragedi letusan bom nuklir di Hiroshima, teks “PIKA” atau “PIKADON” yang artinya kurang lebih “kilatan atau ledakan cahaya” secara langsung merujuk kepada bencana bom nuklir yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Selain merenggut sekitar 80.000 nyawa, bencana ini juga ikut menandai kekalahan Jepang dalam perang dunia ke-2 dan menorehkan luka yang begitu mendalam bagi sebagian besar masyarakatnya.
Karena teks ini, karya kelompok ChimPom kemudian dianggap telah menyebabkan kontroversi sosial yang memancing kritisisme dan perdebatan sengit sehingga pada akhirnya rencana pameran tunggal mereka di Hiroshima City Museum of Contemporary Art (Hiroshima MOCA) harus dibatalkan. Namun begitu, karya mereka tampaknya telah berhasil membuka kembali peluang untuk terus membicarakan berbagai dampak yang telah dihasilkan oleh penggunaan teknologi nuklir untuk kepentingan militer. Barangkali karya ChimPom merupakan salah satu contoh bagaimana praktik seni kontemporer dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membuka ruang dialog dan membicarakan berbagai masalah sosial yang dianggap sensitif di ranah publik.
Dalam nuansa yang berbeda, sebentuk dimensi ketegangan politik juga tercermin melalui karya Apichatpong Weerasethakul. Karya videonya yang berjudul “Phantoms of Nabua” diambil di perkampungan Nabua yang sempat menjadi arena pertarungan kekuasaan antara Thailand dan komunitas petani komunis setempat. Daerah ini berada di bawah pengaruh Laos dan Uni Soviet pada sekitar tahun 1960 s/d awal 1980-an. Akibat situasi konfilk yang berkepanjangan, daerah ini juga kerap dikenal sebagai “kampung janda” (widow town) karena banyak diantara penduduknya yang memilih untuk melarikan diri ke tengah hutan dan meninggalkan anak istri mereka. Karya video Apichatpong yang berdurasi sekitar 30 menit dibuka dengan sambaran halilintar yang hadir secara bergantian, sebelum kemudian menampilkan adegan sekelompok pemuda yang asyik bermain bola api. Secara sekilas karya ini menampilkan kombinasi aneh yang mempertemukan misteri, ketegangan, rasa getir, gairah dan kegembiraan. Dalam pengantar kuratorial yang ditulis oleh Gridthiya Gaweewong, dituliskan bahwa selama ini Apichatpong dikenal sebagai pembuat karya video yang kerap menyampaikan berbagai persoalan sosial dan ingatan kultural, terutama bagi komunitas subkultur dan kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Perdebatan dalam Forum
Sebagai bagian dari program A3, panitia penyelenggara menggelar sebuah konferensi dalam wadah Asia Art Forum 2010 sejak tanggal 9 s/d 15 April 2010. Program ini mengundang lebih dari 50 pembicara yang memiliki latar belakang disiplin ilmu dan kebangsaan yang beragam. Beberapa diantaranya adalah Ruth Knowles (Kepala Global Marketing & Investor Relation, The Fine Art Fund, UK), Zhang Qing (Direktur Shanghai Museum of Art, CN), Huang Du (Kurator independen, CN), Frédéric Paul (Direktur Contemporary Art Centre, FR), Chaitanya Sambrani (Ahli teori seni, AU), Fumihiko Sumitomo (Kurator independen, JP), Heiner Holtappels (Direktur Montevideo, NL), Gridthiya Gaweewong (Direktur The Jim Thompson Art Center, TH), Menene Gras Balaguer (Direktur Casa Asia, ES), dsb. Secara spesifik pembicaraan dalam konferensi ini dibagi ke dalam beberapa tema, yang antara lain adalah Art & Capital, Oriental Metaphor, Art & Technology dan Media Archive Network. Selain itu, ada kuliah umum yang secara khusus membahas perkembangan seni kontemporer di wilayah Asia. Selama hampir satu minggu, khalayak luas diajak untuk terlibat secara langsung untuk mencermati berbagai aspek yang terkait dengan perkembangan seni kontemporer di Asia, mulai dari tinjauan sejarah, teori, sampai pada keterkaitan praktik seni kontemporer dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi.
Dalam pengantar yang dibacakan pada sesi pembukaan, Suh Jinsuk menguraikan bagaimana perkembangan seni kontemporer di Asia saat ini telah berada di bawah pengaruh kapitalisme global, sehingga perkembangan seni kontemporer juga menjadi arena proses komodifikasi finansial yang tidak jauh berbeda dengan komoditas di pasar modal. Fenomena ini diuraikan oleh Ruth Knowles yang melihat aktifitas seni sebagai sebuah proses penciptaan nilai kapital (capital creation), sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah aset ekonomi (new asset class) yang memiliki nilai investasi yang valid. Namun begitu, hal ini bukan berarti pasar seni kontemporer tidak memiliki persoalan. Menurutnya pasar seni kontemporer merupakan wilayah yang tidak memiliki regulasi yang jelas (unregulated market), sehingga tidak mudah untuk menetapkan nilai finansial dari sebuah karya seni. Oleh karena itu, upaya pengembangan pasar seni kontemporer harus dilakukan secara profesional dan hati-hati, selain membutuhkan sokongan kebijakan, strategi dan keberadaan beberapa institusi penunjang semisal museum, galeri, balai lelang, institusi pendidikan sampai pada industri media dan publikasi.
Menyambung hal ini, Massimiliano Gioni (Direktur artistik Gwangju Biennale 2010) menyatakan bahwa saat ini seni sudah menjadi bagian dari industri citra (image making industry). Namun begitu, seni juga merupakan sistem representasi yang memiliki dimensi sosial sehingga beririsan dengan berbagai aspek yang terkait dengan hidup kita, terutama dari segi estetika, sejarah, nilai-nilai, etika, moralitas dan juga politik. Hal ini misalkan tercermin melalui uraian yang disampaikan oleh Carol Lu Yinghua (Kritikus seni, CN), yang memberikan gambaran bagaimana dominasi pasar seni kontemporer di Cina juga ikut mempengaruhi mekanisme penulisan sejarah seni di sana. Dalam hal ini perlu disadari bahwa dominasi pasar yang berlebih juga dapat membahayakan integritas medan sosial seni sehingga dapat memperkecil peluang lahirnya gagasan-gagasan alternatif. Selain itu hegemoni pasar juga dapat memiliki kecenderungan untuk mengeliminasi keberagaman ekspresi artistik, terutama bagi karya seni yang mengedepankan pendekatan konseptual dan wacana intelektual. Idealnya kekuatan kapital yang beroperasi di ranah ekonomi juga dapat bersanding secara harmonis dengan dimensi sosial, intelektual, kultural atau bahkan spiritual. Dalam konteks ini, sebagian peserta berpendapat bahwa perkembangan pasar seni kontemporer di Asia akan kehilangan arah dan tujuannya yang hakiki apabila tidak memiliki visi dan integritas yang teruji.
Perdebatan kritis juga mengemuka dalam sesi Oriental Metaphor yang digelar untuk mengartikulasikan kecenderungan bahasa artistik yang dianggap mampu merepresentasikan identitas Asia. Sesi ini dibuka dengan presentasi Lee Youngchul (Direktur Nam Jun Paik Art Center) yang menelusuri jejak kecenderungan ekspresi artistik Nam Jun Paik dalam makalahnya yang berjudul “Yellow peril! C’est moi”. Dalam salah satu uraiannya, Lee menyebutkan bagaimana Nam Jun Paik kerap disebut sebagai seorang teroris kultural (cultural terrorist) karena memiliki intensi untuk menghancurkan berbagai makna simbol dan metafor yang telah mapan di dalam karya-karyanya. Namun begitu, justru karena hal ini Nam Jun Paik kemudian diakui sebagai seniman pendobrak yang mampu memperlihatkan kecenderungan baru, terutama di bidang seni media dan video. Pembicaraan ini kemudian dilanjutkan oleh Chaitanya Sambrani yang menelusuri kecenderungan bahasa artistik dari beberapa seniman Asia seperti Subodh Gupta (IN), Tallur L.N. (IN/ KR) dan Phaptawan Suwannakudth (TH/ AU). Menurutnya penggunaan simbol dan metafor pada beberapa karya seniman ini tidak pernah memiliki makna yang utuh dan selalu membutuhkan catatan kaki yang komperehensif karena artikulasi bahasa artistik yang mereka kembangkan memiliki lapisan kompleksitas yang luar biasa. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bahasa ekspresi artistik selalu memiliki kecenderungan untuk melampaui batas-batas teritori geografis, politik dan budaya.
Hal yang senada juga disampaikan oleh Nancy Adajania (Ahli teori budaya & kurator independen, IN), yang menyarankan untuk memeriksa kembali berbagai bentuk penggunaan simbol dan metafor yang selama ini dianggap merepresentasikan kecenderungan artistik seniman Asia. Dalam penjelasannya, Nancy menggunakan terminologi critical trans-regionalism sebagai sebuah diskursus kritis yang perlu untuk dikembangkan agar kita dapat menghindari pemahaman yang superfisial tentang keberadaan simbol, metafor atau struktur bahasa dalam sistem representasi yang merujuk pada sebuah entitas budaya dalam lingkungan geografis tertentu. Menurutnya, pendekatan semacam ini sangat diperlukan untuk melawan proses dikotomi dan hegemoni yang justru dapat menghilangkan peluang bagi terjadinya interaksi, dialog dan kolaborasi. Lebih jauh, upaya semacam ini juga sangat dibutuhkan untuk memperkaya sistem bahasa dan pengetahuan yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan kesetaraan. Pola relasi timur (orient) dan barat (occident) yang berkembang selama ini tampaknya sudah kadung terjebak ke dalam sistem berfikir logika biner yang justru berpeluang untuk melanggengkan proses kolonialisasi secara simbolik. Dalam hal ini dipandang perlu untuk melihat kembali hubungan timur dan barat sebagai sebuah teritori kultural yang netral dan ranah politik budaya yang terbebas dari klaim sistem kepemilikan (politics of dispossession).

Seni dan Teknologi
Perkembangan teknologi digital di abad ke-21 tak pelak lagi telah melahirkan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Melalui perkembangan teknologi digital, mekanime produksi informasi dan pengetahuan telah mengalami perubahan secara radikal. Dalam konteks ini, praktik seni kontemporer semakin mengalami perluasan dan tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek yang terkait dengan perkembagan teknologi. Sejak manusia primitif melukis di dalam gua, selalu ada aspek-aspek teknis yang secara inheren melekat dalam mekanisme produksi karya artistik dan ekspresi budaya. Hal ini mengemuka pada sesi seminar Art & Technology yang dimoderasi oleh Fumihiko Sumitomo (Kurator independen, JP). Dalam presentasi yang disampaikan oleh Yukiko Shikata (Kurator independen, JP), digambarkan bagaimana perkembangan teknologi media telah menjadi semacam ekstensi indera (extended senses) yang banyak dimanfaatkan oleh para seniman untuk mencermati berbagai situasi dan persoalan yang ada di sekeliling mereka. Dalam hal ini, teknologi juga memiliki peran yang penting dalam melahirkan berbagai pendekatan baru dalam proses penciptaan dan penyebaran karya artistik di kalangan masyarakat luas.
Perkembangan teknologi media juga melahirkan berbagai bentuk pemahaman dan pendekatan yang baru dalam sistem representasi dan simulasi. Hal ini secara rinci dijelaskan dalam materi berjudul “My Cortext: Media Art and the Sensory Experience”, yang disampaikan oleh Prof. Yoon Joonsung (Global School of Media, Soongsil University, KR). Menurutnya wilayah irisan antara seni dan teknologi telah memberikan definisi yang baru bagi dunia pengalaman, identitas dan benda-benda, termasuk ruang dan waktu. Beda pengertian antara karya orisinil/reproduksi ataupun material/imaterial menjadi begitu cair karena teknologi media telah memungkinkan kita untuk menterjemahkan sensor indrawi menjadi data dan informasi yang dapat direproduksi dan disebarkan dengan mudah. Melalui aspek-aspek keterbukaan, konektifitas dan interaksi, pengalaman artistik juga telah mengalami perluasan makna, terutama ketika setiap orang dapat terlibat secara aktif dalam proses penciptaan dan penyebaran karya seni. Merujuk pada pemikiran Hans Belting dalam bukunya yang berjudul “Art History After Modernism” (2003), Prof. Yoon menyatakan bahwa meleburnya berbagai batasan yang sebelumnya berdiri secara mapan akan menjadi tantangan tersendiri bagi seniman dan medan sosial seni (art world) di masa depan.
Terkait dengan uraian di atas, Jen Mizuik (Direktur Experimenta, AU) memberikan gambaran bagaimana perkembangan di bidang seni dan teknologi juga berimplikasi pada mekanisme presentasi yang menjadi semakin spesifik dan membutuhkan konteks yang tepat. Hal ini misalkan tercermin dalam penyelenggaraan Experimenta, sebuah bienalle internasional seni media yang diselenggarakan di kota Melbourne pada tanggal 12 Februari s/d 14 Maret 2010. Perhelatan ini menampilkan sekitar 25 karya dari para seniman yang berasal dari Australia, Jepang, Austria, India, Jerman, Kanada, Prancis, Taiwan dan Inggris. Selain menyelenggarakan pameran, Experimenta juga menggelar serangkaian kegiatan pemutaran film & video, lokakarya, seminar, diskusi, performance dan konser musik. Salah satu aspek yang penting dari perhelatan ini adalah aktifitas produksi informasi dan pengetahuan yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat secara luas. Sebagai hasilnya, penyelenggaraan Experimenta berhasil melibatkan sekitar 100.000 pengunjung yang datang bergantian selama kegiatan ini berlangsung. Dalam kesempatan ini, publik luas mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan berbagai aspek yang terkait dengan perkembangan di bidang seni dan teknologi.
Perkembangan teknologi media yang berkembang sedemikian pesat tak luput dari persoalan dan kritik. Pada salah satu sesi presentasi, Dr. Bernhard Serexhe (Kurator kepala ZKM Media Museum, DE) menguraikan bahwa teknologi media telah menawarkan sebuah arena baru dimana informasi dan pengetahuan dapat diakses dan disebarkan oleh siapapun dengan mudah. Namun begitu, teknologi juga menawarkan representasi kenyataan yang telah mengalami proses seleksi dan kodifikasi. Sebagai hasilnya, kenyataan tidak lagi tampil dalam wujudnya yang utuh, melainkan telah dipecah ke dalam berbagai versi. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa saat ini kita semakin sulit untuk berinteraksi dengan kenyataan secara total dan otentik. Dunia pengalaman telah digantikan oleh gambaran yang disebarkan melalui berbagai media yang ada di sekeliling kita. Di lain pihak, penggunaan media digital dan internet juga telah memungkinkan terjadinya aktifitas pengawasan yang melekat (surveillance), melalui penggunaan teknologi filter informasi yang kebanyakan dikembangkan untuk kebutuhan militer dan industri. Untuk itu dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi media juga memiliki aspek-aspek politis berupa kontrol dan hegemoni yang beroperasi secara halus. Dalam konteks ini barangkali seni dapat mempertegas kembali posisinya sebagai wahana inovasi, kritik dan refleksi.
Kyai Gede Utama, April 2010
* Penulis adalah seniman, bekerja untuk Common Room Networks Foundation (Common Room)