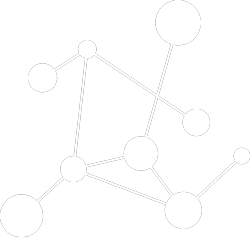Foto: Idhar Resmadi
Pantun Sunda merupakan seni pertunjukan cerita sastra Sunda lama yang disajikan dalam paparan, dialog, dan nyanyian. Seni pantun dilakukan seorang juru pantun diiringi kacapi yang dimainkannya sendiri. Seni pantun Sunda berbeda dengan pantun Melayu yang serupa sindiran dalam tradisi Sunda (puisi yang terdiri dari dua bagian, sampiran dan isi).
Dalam naskah Siksa kandang Karesian (1518M) dipaparkan pantun digunakan sejak zaman Langgalarang, Banyakcatra, dan Siliwangi. Asalnya cerita pantun seputar kisah kegagahan raja-raja di atas. Pada perkembangannya cerita pantun terus bertambah. Kita pasti tak asing dengan Lutung Kasarung, Langgasari, Ciung Wanara, Mundinglayadikusumah, Dengdeng Pati Jayaperang, Ratu Bungsu Kamajaya, Sumur Bandung, Demung Kalagan, dll. Seni tua usianya ini melahirkan beberapa ahli pantun seperti Rd. Aria Cikondang dari Cianjur (abad 17), Aong Jaya Lahiman dan Jayawireja (abad 19), Uce dan Pantun Beton Wikatmana dari Bandung (awal abad 20) dan Ki Buyut Rombeng dari Bogor.
Seni pantun Sunda umumnya merupakan kisah yang disampaikan oleh pendongeng profesional pada zamannya yang seringkali berkelana dari desa ke desa untuk menyampaikan ceritanya kepada semua orang. Tujuan sang juru pantun bertutur adalah untuk mengajarkan agama, kepercayaan, sejarah, mitologi, moral, dan tata krama. Sepanjang abad ini, dongeng-dongeng para juru pantun lambat laun berubah menjadi cerita anak-anak. Salah satu pantun Sunda yang sangat terkenal adalah Lutung Kasarung. Dengan syair yang panjangnya lebih dari 1000 baris, kisah yang berasal dari abad 15 ini begitu populer hingga termasuk kisah pertama yang difilmkan di Indonesia pada 1926.
Pantun disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama sajian untuk hiburan dan yang kedua merupakan sajian ritual (ruwatan).Sebagai sajian hiburan, pantun diceritakan atas permintaan penaggap. Sebagai sajian ruwatan, pantun ditampilkan sama dengan cerita wayang, seperti Batara Kala, Kama Salah, atau Murwa Kala. Pertunjukan pantun, baik dalam fungsi hiburan maupun ritual, tidak disajikan sembarangan. Sifatnya yang sakral dipertahankan karena bagi masyarakat Sunda membaca dan mendengarkan pantun berisi cerita raja-raja atau leluhur mereka merupakan bentuk penghormatan tersendiri kepada nenek moyang.
Pola pertunjukan pantun tak pernah berubah: penyediaan sesajen, ngukus (membakar kemenyan), mengumandangkan rajah pamunah, babak cerita dari awal hingga akhir, dan penutupan dengan mengumandangkan rajah pamungkas. Pertunjukan biasanya diiringi alat jusik kacapi. Awalnya, kacapi yang dipergunakan sangatlah sederhana seperti kacapi Baduy yang hanya berdawai 7 kawat. Seiring dengan pertumbuhan seni Cianjuran, kacapi kecil itu digantikan dengan kacapi gelung (tembang) dan akhirnya kacapi siter. Laras yang dimainkan mengiringi pantun biasanya adalah laras pelog dan salendro.
Sebagai kesenian yang hidup di tatar Sunda sejak zaman purba sampai Islam dan menjadi anutan masyarakat, tak heran jika ungkapan, ajaran, dan petuah ki juru pantun yang terdapat dalam isi pantun adalah pembauran kedua zaman itu. Selain banyak ungkapan-ungkapan yang berasal dari budaya Islam seperti istighfar, takbir, dll., terdapat pula ungkapan khas Hindu-Budha seperti ka dewata, ka pohaci, ka para karuhun, buyut, dan lain-lain.
Harus diakui, dewasa ini, kondisi seni pantun sangat memprihatinkan. Walaupun seni pantun masih dapat bertahan sebagai seni yang adiluhung, tetap saja telah terjadi pergeseran terutama dalam fungsinya dari yang sakral menjadi profan.
*penulis adalah penulis buku “Myself Scumbag”, guru sejarah, dan musisi Karinding Attack