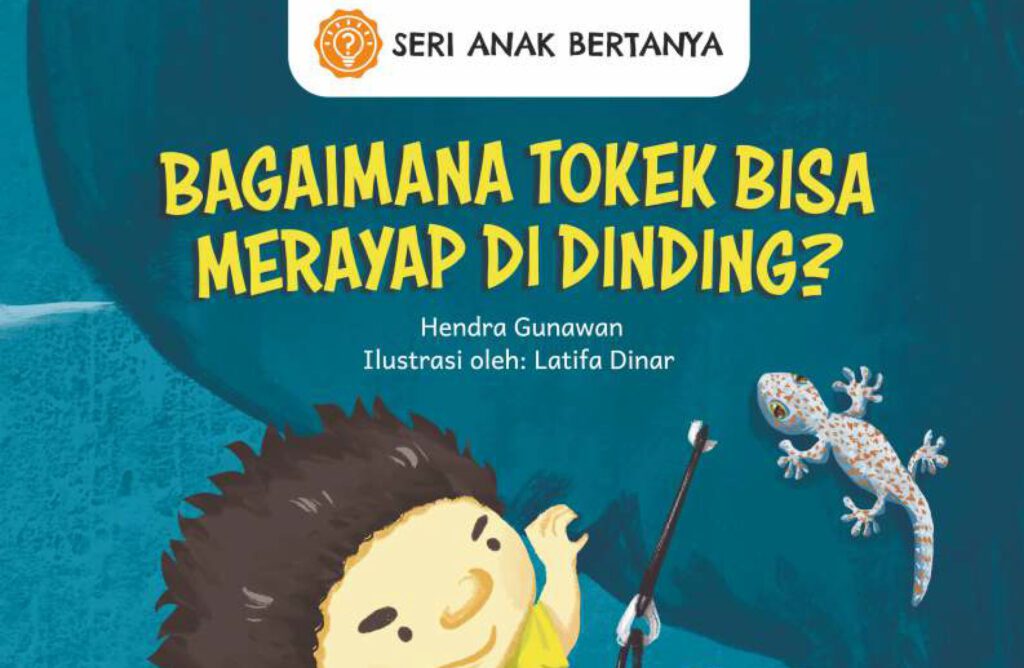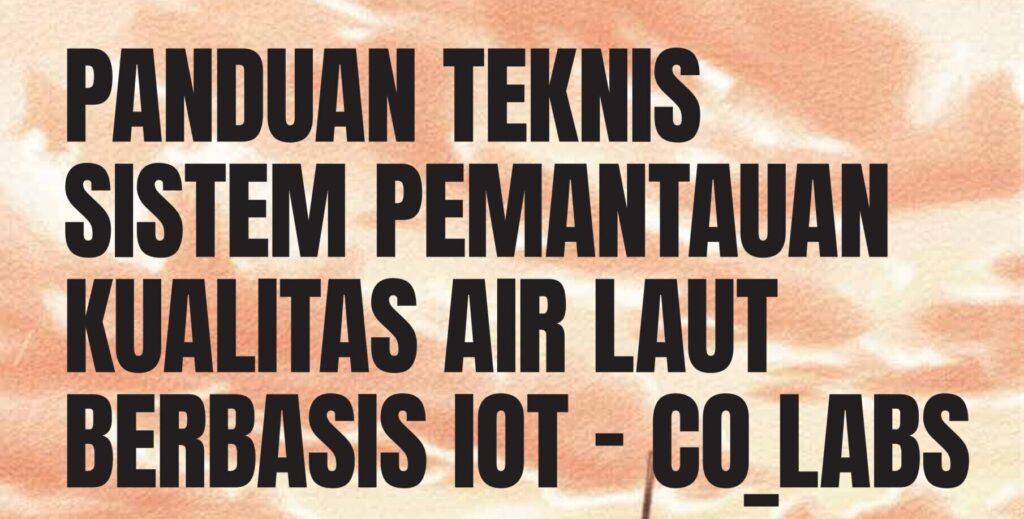Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Rural ICT Camp 2025 sesi dialog kebijakan berlanjut pada diskusi bertajuk Berbagi Praktik Kebijakan, Penyelarasan, dan Sesi Pemantauan Kebijakan (Policy Tracker) di Ruang Edelweis, Wisma Hijau, Depok pada Kamis (25/9/2025). Dipandu oleh asisten peneliti Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (CMCI) Fikom Unpad, Rudi Dwi Hartanto sesi dialog ini menjadi ruang strategis bagi peserta untuk mendalami berbagai aturan dan perizinan yang memengaruhi operasional SIK di daerah, serta memperkuat kemampuan komunitas dalam memantau dan menyelaraskan kebijakan melalui “policy tracker”.
Rudi Dwi Hartanto membuka sesi dengan menegaskan pentingnya memahami konteks hukum yang mengatur inisiatif internet komunitas. “Kita akan membahas sejauh mana teman-teman mengetahui aturan yang bisa dimanfaatkan, menjadi celah, atau membuka kemungkinan baru agar SIK bisa lebih diakui oleh pemerintah, dari desa hingga nasional,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala CMCI Fikom Unpad, Subekti Priyadharma menambahkan bahwa proses advokasi kebijakan membutuhkan pembagian peran yang jelas di antara anggota komunitas, mulai dari advokasi, gender, hingga kapasitas teknis. Ia menekankan pentingnya adaptasi gerakan internet komunitas terhadap regulasi yang ada, tanpa kehilangan semangat kemandirian.
“Modal tiap komunitas berbeda, jadi pendekatannya juga harus disesuaikan. Yang penting, kita tahu celahnya dan cara adaptasinya,” tegas Subekti.
Sesi dilanjutkan dengan pemaparan oleh Nasrun Mustafa dari SIK Taliabu yang berbagi praktik baik tentang pengurusan legalitas melalui BUMDes. Menurutnya, bekerja sama dengan BUMDes menjadi solusi efektif agar kegiatan SIK memperoleh legitimasi tanpa biaya besar.

Nasrun menjelaskan langkah-langkah administratif yang dilakukan, mulai dari musyawarah desa, penyusunan notulen dan daftar hadir, hingga pendaftaran di portal BUMDes Kemendesa.
“Legalitas BUMDes tidak seperti PT yang perlu notaris. Cukup lewat portal Kemendesa, tiga hari sudah keluar izin resminya,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dengan struktur hukum yang sudah ada di desa agar SIK tidak dianggap melanggar aturan.
Sesi berlanjut dengan diskusi antar kelompok yang membahas tantangan dan peluang legalisasi SIK serta penyusunan dan pengelolaan policy tracker untuk memantau aturan yang berlaku. Setiap kelompok memaparkan pengalaman nyata di lapangan, mulai dari perizinan yang rumit, kurangnya dukungan pemerintah desa, hingga kebutuhan akan bentuk hukum yang paling sesuai bagi komunitas.

Andi dari SIK Maros menilai bahwa kelompok masyarakat adalah bentuk yang paling sederhana dan murah untuk diakui secara hukum. “Kelompok itu legal dan diakui dari desa sampai kementerian. Tidak perlu biaya, asal didukung kepala desa,” katanya.
Sementara itu, Ajier dari SIK Pulo Aceh membahas kendala kurangnya dukungan pemerintah daerah serta mahalnya biaya legalisasi. Ajier menyoroti perlunya rekognisi langsung dari Kominfo atau Kemendes agar SIK diakui sebagai penyedia layanan digital berbasis komunitas.
“Harus ada SK resmi yang mengizinkan SIK beroperasi. Ini penting untuk legalitas dan keberlanjutan,” ujarnya.

Saat sesi kedua berlangsung, diskusi difokuskan pada strategi membangun policy tracker, alat untuk mencatat, memantau, dan menganalisis kebijakan yang berdampak pada internet komunitas. Beberapa hasil temuan di lapangan mengerucut soal pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat desa dalam setiap kebijakan. Selain itu, penggunaan media sosial dan media massa juga disarankan sebagai sarana publikasi hasil advokasi agar dapat menjangkau pemerintah kabupaten hingga provinsi.
Menutup sesi tersebut, Subekti menyinggung potensi pemanfaatan Dana BOS Afirmatif dan BOS Kinerja untuk mendukung infrastruktur digital di sekolah-sekolah terpencil.
“BOS Afirmatif bisa digunakan untuk penyediaan router dan sarana digital, tapi syaratnya harus ada jaringan internet. Ini bisa jadi peluang bagi teman-teman SIK yang sudah menghadirkan koneksi di wilayahnya,” jelasnya.
Subekti menegaskan bahwa keberhasilan advokasi Internet Komunitas tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kecermatan memahami dan menavigasi regulasi. Dengan adanya policy tracker, komunitas kini memiliki alat untuk memantau kebijakan, mengukur progres advokasi, dan memperkuat posisi mereka dalam dialog dengan pemerintah.
“Kita ingin Internet Komunitas tidak hanya eksis, tapi juga diakui secara sah dan berkelanjutan,” tutup Subekti.***