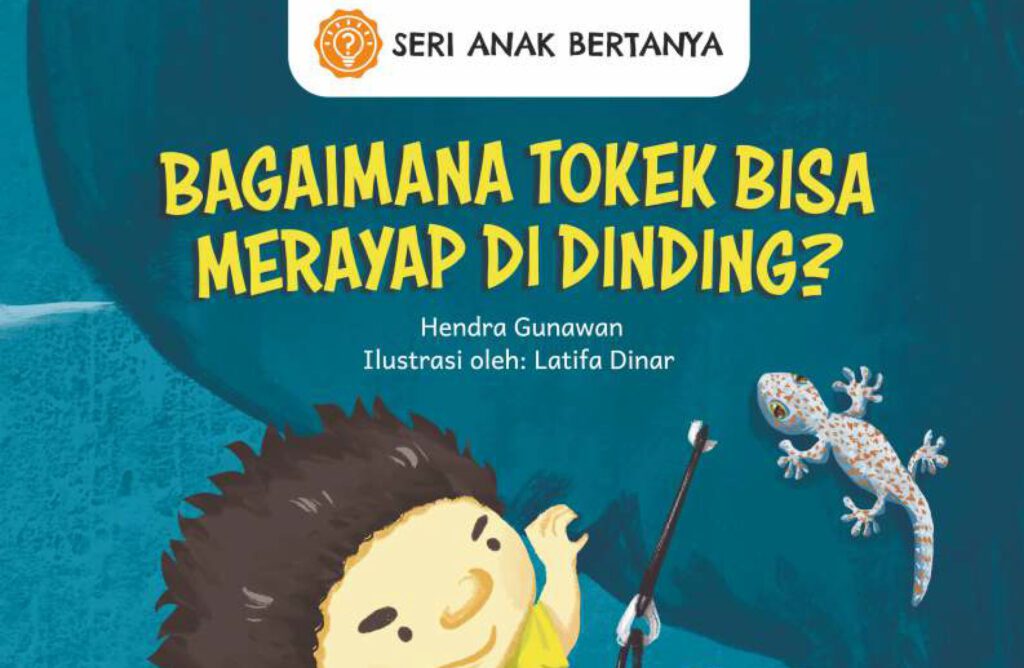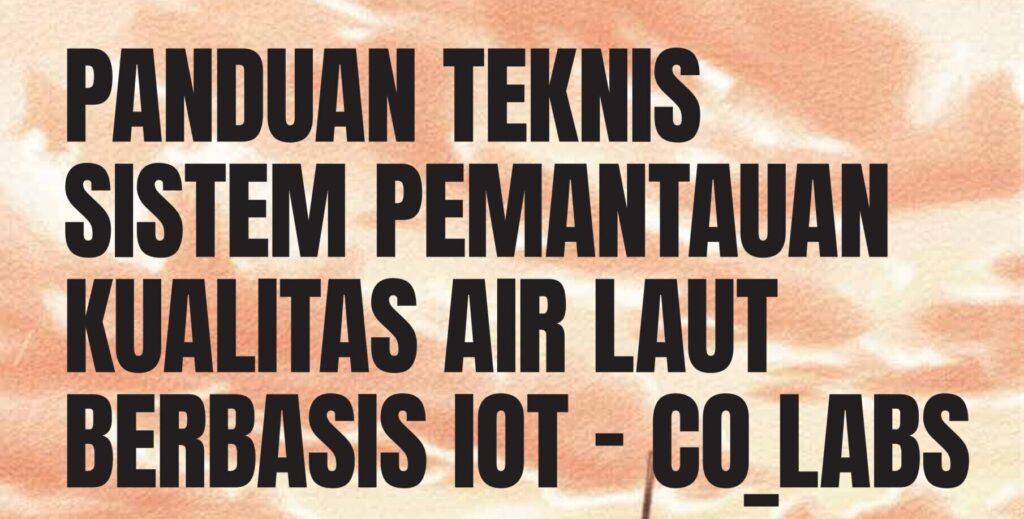Dalam rangkaian Rural ICT Camp 2025 sesi lanjutan dialog kebijakan bersama Rembuk Nusa “Berbagi Praktik Kebijakan dan Jalan Menuju Rekognisi Internet Komunitas Bermakna” digelar Ruang Edelweis , Wisma Hijau, Depok pada Jumat (26/9/2025). Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyatukan strategi advokasi, menyusun narasi bersama, dan memperkuat langkah-langkah kebijakan menuju pengakuan resmi bagi inisiatif Internet Komunitas di Indonesia.
Dalam pembukaannya Direktur Common Room, Gustaff H. Iskandar menyoroti pentingnya modal sosial dan kultural sebagai faktor penentu keberhasilan inisiatif Internet Komunitas. Ia menyebut sejumlah contoh nyata di berbagai daerah seperti Taliabu Maluku Utara yang menampilkan dukungan lengkap dari pemerintah pusat hingga desa, Ciptagelar Sukabumi dengan model pengelolaan adat yang mandiri, Ciracap Sukabumi yang memperlihatkan semangat kewirausahaan digital, Sukadana Lombok di mana kepemimpinan perempuan menjadi kunci ketahanan komunitas, Desa Tembok Bali di mana kepala desa menjadi motor penggerak utama keberhasilan digitalisasi lokal.
Menurut Gustaff, “Keberhasilan di setiap wilayah tidak bisa diseragamkan. Yang menentukan justru kemampuan masyarakat setempat dalam memimpin, berorganisasi, dan mengelola sumber daya mereka sendiri.”

Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (CMCI) Fikom Unpad, Subekti Priyadharma menjelaskan pentingnya melakukan inventarisasi regulasi di berbagai level, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteriagar dapat memetakan ruang advokasi yang realistis.
Selain itu, muncul gagasan untuk membangun mekanisme pemantauan kebijakan (policy tracking system) yang dinamis, mengingat perubahan regulasi di bidang digital sering terjadi tanpa konsultasi publik yang memadai.
“Kita tidak bisa hanya menunggu regulasi datang dari atas. Kita perlu terus memantau, mengisi ruang, dan memastikan narasi komunitas tetap terdengar dalam kebijakan,” tegas Subekti.
Salah satu topik hangat yang dibahas adalah rencana Regulatory Sandbox skema uji coba kebijakan yang tengah dipertimbangkan oleh Ditjen Infrastruktur Digital Kominfo.
Kordinator Peningkatan Kapasitas Regional Asia LocNet, Akhmat Safrudin menilai sandbox ini bisa menjadi pintu masuk penting bagi pengakuan formal Internet Komunitas, namun perlu dikawal agar tidak justru menjadi alat pembatas baru.

“Sandbox bisa memberi ruang fleksibel untuk eksperimen kebijakan, tapi klausulnya harus jelas agar tidak menekan komunitas. Jangan sampai semangat pengakuan berubah menjadi pembatasan,” ujarnya.
Diskusi juga menyinggung perlunya badan koordinasi lintas pemangku kepentingan yang dapat menjadi jembatan antara komunitas dan pemerintah, sekaligus memayungi berbagai model operasional Internet Komunitas di daerah.
Forum Rembuk Nusa menegaskan bahwa strategi advokasi harus tetap berakar pada pengalaman lapangan namun mampu diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan yang mudah dipahami oleh pemerintah.
“Pemerintah membutuhkan narasi yang konkret dan terukur. Maka, advokasi kita perlu menampilkan small wins dari lapangan — seperti kisah Taliabu, Ciracap, dan Ngata Toro — sebagai bukti nyata bahwa Internet Komunitas layak diakui,” jelas Gustaff.
Peserta sepakat bahwa storytelling berbasis hasil nyata menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi advokasi dan membangun kredibilitas di mata regulator.

Direktur Eksekutif ICT Watch Indriyatno Banyumurti berbagi pengalaman tentang tantangan advokasi literasi digital yang hingga kini belum memiliki dasar regulasi kuat. Menurutnya, tanpa kerangka hukum, program literasi digital sering hanya dianggap sebagai gerakan sosial tanpa kesinambungan kebijakan.
Gustaff H. Iskandar kembali menjelaskan bahwa saat ini komunitas hanya bisa membeli bandwidth dengan harga ritel, bukan grosir (wholesale), karena tidak diakui sebagai penyedia resmi. Hal ini membuat biaya operasional tinggi dan menghambat keberlanjutan usaha sosial digital di tingkat desa.
Selain itu, posisi komunitas masih lemah secara hukum karena UU Telekomunikasi hanya mengakui entitas berbentuk BUMN, BUMS, atau PT besar. Akibatnya, inisiatif warga seperti Internet Desa atau RT/RW Net sering kali berjalan di area abu-abu secara legal.
Sebagai hasil diskusi, peserta merumuskan lima agenda strategis untuk memperkuat posisi Internet Komunitas dalam kebijakan nasional dan lokal yaitu Penyusunan Narasi dan Terminologi Bersama untuk menyepakati istilah “Internet Komunitas” dan bahasa advokasi yang konsisten. Kedua, Pembangunan Regulatory Sandbox yang merumuskan desain kebijakan uji coba yang berpihak pada komunitas, terutama di wilayah 3T. Ketiga, Pemetaan Jalur Legalitas dan Kebijakan Lokal yang menyusun panduan berbagai bentuk kelembagaan (BUMDes, koperasi, PT, atau kelompok masyarakat). Keempat, Eksplorasi Skema Pendanaan Alternatif termasuk pemanfaatan Dana BOS Afirmatif untuk konektivitas dan literasi digital di sekolah-sekolah 3T. Terakhir, Pembentukan Badan Koordinasi Advokasi untuk menyelaraskan strategi antarwilayah dan menjembatani dialog dengan pemerintah pusat.

Tujuan akhir dari seluruh upaya advokasi ini bukan hanya legalitas formal, tetapi pengakuan yang bermakna (meaningful recognition) terhadap hak warga untuk mengelola infrastruktur digitalnya sendiri. Dengan semangat kolaborasi antara komunitas, akademisi, dan pemerintah, Rembuk Nusa menjadi tonggak penting menuju kebijakan Internet Komunitas yang lebih inklusif, adil, dan berakar dari inisiatif masyarakat sendiri.***