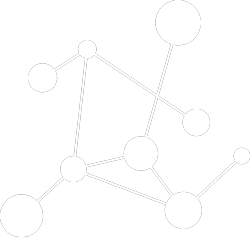PEMBUKAAN PAMERAN
Balai Kota
Jl. Perintis Kemerdekaan (Pagar Selatan)
Jumat, 14 Mei 2010
Pukul 15.00 WIB
Babakan Asih
Lapangan KARTOEN ERVAT, Babakan Asih RT 04/ RW 01 (Masuk lewat Jl. Haji Topek)
Sabtu, 15 Mei 2010
Pukul 9.00 WIB
Peta Babakan Asih
View Babakan Asih in a larger map
* Pameran berlangsung dari 14 s/d 28 Mei 2010
Kota yang Keluyuran Malam Hari
Hawe Setiawan | Penulis lepas
Download .pdf
KOTA sesungguhnya terbuat dari lampu-lampu, sosok-sosok yang bergerak seperti hantu, dan seberkas hasrat untuk menaklukkan kegelapan. Sejak orang menyalakan lampu gas di abad ke-19, terlebih-lebih sejak energi listrik merambat ke seantero bumi, orang membangun kehidupan malam di wilayah-wilayah urban. Begadang dirayakan baik oleh lagu dangdut maupun oleh program televisi. Kelelawar menyingkir, dan kunang-kunang berakhir. Kota adalah kelelawar. Kota adalah kunang-kunang.
“Pencahayaan kota mengubah cara orang memikirkan—dan karena itu menghidupi—malam. Kegelapan, yang begitu lama merintangi kegiatan manusia, seketika jadi rangsangan,” tulis William Chapman Sharpe dalam bukunya, New York Nocturne: the City After Dark in Literature, Painting, and Photography, 1850–1950 (2008).
Kota yang dirangsang cahaya adalah kota yang menghardik mati listrik. Lalu-lintas, donor darah, dan bursa efek tidak boleh macet. Adapun gulita bisa menghilangkan dunia persepsi seketika. Kota tidak mau macet, juga tidak mau meraba-raba dalam kegelapan. Kota takut oleh kegelapan. Bahkan di mal-mal yang terus bermunculan neon ribuan watt seakan ingin memperpanjang siang. Orang yang mengunjungi mal baru menyadari hadirnya kegelapan manakala sudah kembali ke jalan.
Tapi benarkah kegelapan dapat ditaklukkan? Rasa-rasanya, tidak. Bahkan pada saat-saat tertentu orang sepertinya justru merindukan kegelapan. Setidak-tidaknya, orang masih mencari suram dan redup di sudut-sudut kafe atau taman kota, mungkin buat mengelola cinta, puisi, atau urusan lainnya. Yang paling nyata, kiranya, adalah semacam ruang antara: gelap di satu sisi, terang di sisi lain. Di antara gelap dan terang, kita membangun persepsi tiada henti sebagaimana yang kita wujudkan melalui seni rupa dan fotografi.
***
ADA kunang-kunang dari Prancis, namanya Romain Osi. Bulan ini ia berkunjung ke Bandung. Fotografer kelahiran Paris tahun 1980 ini memotret kota ini malam hari, kemudian memamerkan karyanya di ruang-ruang terbuka. Centre Culturel Français de Bandung bersama Common Room Networks Foundation menyelenggarakan kegiatan ini. Judulnya, “Keluyuran”.
Sebelum ke Bandung, Romain mengunjungi Phnom Penh, Rio de Janeiro, Havana, dll. Orang menyebutnya “fotografer kelana” (photographe de l’errance). Ia memotret kota demi kota, bergerak dari suasana malam yang satu ke suasana malam yang lain. Jika kita mengunjungi websitenya (http://www.romainosi.com), kita dapat melihat hasil-hasil perjalanan malamnya, yang beberapa di antaranya dipamerkan pula di di Galerie Esp’Art, CCF de Bandung, dengan tajuk “Urban Dream”.
Dalam hal udar-ider di Bandung untuk berkarya, Romain adalah tamu Prancis kesekian. Pada akhir dasawarsa 1990-an, misalnya, Marc Le Moullec berkeliling kota, masuk keluar gang, mengendarai sepeda motor Jepang. Ia mencatat nama-nama jalan, permukiman, dan kawasan. Hasilnya adalah atlas Kota Bandung. Dengan cara serupa, ia pun membuat atlas Surabaya dan Jakarta.
Romain sendiri, tentu saja, tidak membuat peta. Sekiranya peta disebut model tata ruang, fotografer memasuki ruang itu sendiri. Berbekal kamera digital, sambil membonceng sepeda motor, ia mengunjungi bagian-bagian kota, menuruti kata hati. Di titik-titik tertentu ia berhenti, kadang seperti menunggu sesuatu beberapa saat, kadang pula mengamati-amati keadaan di sekitarnya. Lalu, pada saat yang tepat, ia memotret suasana malam di situ. Kemudian, ia keluyuran lagi ke sudut-sudut lain kota ini. Begitu seterusnya beberapa hari lamanya.
Boleh dikata, ia bekerja tanpa rencana. Apa yang ingin dipotret, atau di mana hendak memotret, tidak ditentukan sebelumnya. Keluyuran itulah yang kiranya terpenting, seperti telah jadi metode tersendiri. Sewaktu keluyuran ia akan tahu di mana mesti berhenti dan ke mana kamera mesti diarahkan.
“Metode saya sepenuhnya mengandalkan perasaan,” kata Romain ketika diajak berbincang pada suatu siang di Bandung, beberapa waktu lalu.
Seperti yang ia lakukan di kota-kota lain di mancanegara, di Bandung pun Romain memilih malam sebagai waktu pemotretan. Bandung sendiri, sebagaimana Solo dan kota-kota lain di Indonesia, niscaya punya cara tersendiri untuk menghidupi malam. Sebuah lagu keroncong ikut merayakan pemandangan “Bandung Selatan di waktu malam”: lampu-lampu yang berserakan bagai jutaan kunang-kunang. Bahkan inilah kota yang salah satu fase sejarahnya diisi dengan imajinasi tentang “lautan api”—kota yang pernah membakar dirinya justru buat menegaskan identitasnya.
Buat sebagian besar warga Bandung, kota ini kiranya hanya dikenal dari jam delapan pagi hingga jam 5 sore. Selepas senja, apalagi setelah larut malam, Bandung seakan mereka tinggalkan sebelum ditemui lagi esok pagi. Adapun Romain, di saat-saat kita tidur dan mematikan listrik, keluyuran di kota ini buat menangkap momen-momen estetik dari ruang yang sedang ditinggalkan banyak orang. Ia menangkap lampu-lampu, sosok-sosok yang seperti hantu, dan latar yang terbungkus semacam kabut halusinasi. Itulah kiranya puisi visual tersendiri—citraan visual yang barangkali tidak begitu kita kenali selama ini.
Dengan cara seperti itu, Romain seperti sedang membaca puisi “Nightwood” karya Djuna Barnes dari tahun 1930-an yang juga dikutip oleh William Chapman Sharpe dalam buku itu tadi: Now the nights of one period are not/the nights of another.//Neither are the nights of one city the/nights of another.
***
FOTO-FOTO karya Romain hasil keluyuran di Bandung dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan sejumlah segi dari wajah Bandung. Temanya meliputi antara lain suasana kehidupan sosial, lanskap kota, dan lingkungan alam. Objek foto sama sekali tidak dimanipulasi. Tekanan diletakkan pada sudut pandang, waktu, dan teknik pemotretan, terutama untuk menghasilkan efek-efek puitik dari hasil pemotretannya.
Dalam foto-foto karya Romain, pepohonan yang tumbuh di punggung bukit Bandung Utara seperti iring-iringan manusia dalam upacara. Rimbunnya dedaunan pohon tinggi bagai gumpalan asap bom atom. Kabel-kabel yang malang melintang pada tiang listrik bak ruwetnya berbagai orientasi di ruang sosial. Bentangan tembok beton di balik gedung-gedung tinggi tak ubahnya dengan tembok pemisah antarkaum. Adapun lanskap kota tampak terhampar di bawah kilatan guntur. Kita pun dapat melihat pusaran cahaya di sekeliling penjaja makanan yang tengah mendorong gerobaknya, barangkali seperti pusaran nasib itu sendiri.
Romain menangkap gerak dan nuansa dari pemandangan yang terhampar di depan dirinya, sedemikian rupa sehingga foto-fotonya sering menimbulkan kesan surrealistis. Dalam foto-fotonya kita memang melihat kota yang sudah kita kenal tapi sekaligus jadi agak asing karena pemandangan yang diperlihatkannya tidak seperti pemandangan yang biasa kita lihat. Kita seperti diajak melihat kota kita dengan sejenis kesadaran baru. Dengan kata lain, wajah kota kita, dengan segala masalahnya, seakan jadi puisi tersendiri.
Foto-foto itu, dalam ukuran besar, kemudian dipajang di ruang-ruang terbuka, antara lain di Babakan Asih, juga di taman sekitar Balai Kota. Dengan demikian, foto-foto itu seakan jadi cermin tersendiri bagi Bandung, dan warga kota yang lalu-lalang di sekitarnya, tentu, dapat ikut mempertimbangkan gambaran kehidupan kota yang tercermin di situ.
***
BANDUNG, dan Priangan umumnya, sejak dulu merupakan salah satu titik persinggungan Asia dengan Eropa yang telah menghasilkan begitu banyak citraan visual seperti drawing, lukisan, karya litografi, dan tentu saja foto. Pada zaman kolonial kegiatan memvisualisasikan alam dan penghuni kawasan Priangan dilakukan baik oleh peneliti kebumian dan kebudayaan maupun oleh seniman. Di antara citraan-citraan visual itu ada yang dijadikan ilustrasi dalam bahan bacaan. Buku Andries de Wilde, De Preanger Regentschappen op Java Gelegen (Keresidenan Priangan di Wilayah Jawa) (1830), misalnya, disisipi 4 gambar hitam putih tentang alam Priangan. Tak sedikit pula foto yang dijadikan kartu pos. Selembar kartu pos bertiti mangsa Desember 1899, contohnya, memperlihatkan sebuah foto bertajuk “Preanger Vrouw” (Gadis Priangan): seorang gadis telanjang dada sedang berdiri seraya menyunggi seikat kayu bakar berlatarkan sebuah lukisan panorama.
Kota Bandung sendiri, yang dalam poster-poster buatan majalah Mooi Bandoeng dijuluki “Europa in de Tropen” (Eropa di Kawasan Tropis), menjelma dari persinggungan orang sini dengan para pendatang dari seberang lautan, tak terkecuali dari lingkungan imperium Prancis. Waktu Bandung mulai dibangun pada 1810 Pulau Jawa termasuk ke dalam kekuasaan Prancis (1809-1811). Konon, Herman Willem Daendels, jenderal pilihan Napoleon Bonaparte dan gubernur di Jawa dari 1808 hingga 1811, menandai awal pembangunan kota ini dengan menancapkan tongkat di titik kilometer nol (Jl. Asia-Afrika kini). Peristiwa itu tampak sebagai rincian tersendiri dari keperkasaan tangan Daendels yang membentangkan jalan 1000 kilometer dari Anyer ke Panarukan. Adapun di antara berbagai “warisan budaya” yang harus dirawat di kota ini tak lain dari gedung-gedung putih peninggalan Belanda.
Interaksi antarbudaya, tentu, ditopang oleh kesanggupan melakukan perjalanan. Dalam kebudayaan Sunda sendiri, pentingnya perjalanan sesungguhnya ditekankan pula, sebagaimana yang dapat kita carikan rujukannya mulai dari kisah Bujangga Manik (abad ke-16) hingga wawacan Panji Wulung (abad ke-19). Pangeran Jaya Pakuan alias Bujangga Manik melakukan perjalanan spiritual menyusuri pulau Jawa hingga ke Bali, dalam dua kali putaran, seraya mencatat nama-nama tempat. Adapun dalam Wawacan Panji Wulung karya R.H. Moehamad Moesa (1822-1886), yang pertama terbit pada 1876, digubah dalam bentuk puisi terikat, berupa asmarandana, petuah tentang hal itu berbunyi: Kieu wurukna ki patih, hé ki Panji anak bapa, ayeuna agus ges gedé, meujeuhna diajar nyaba, ka dayeuh-dayeuh lian, supaya réa panimu, kanyaho nu langka-langka. Panji Wulung sendiri, sebagai pangeran Sunda, bersahabat dengan pangeran Bugis, pergi ke tanah Cempa, Malayu, Keling, dan Patani.
Inilah kiranya yang pada gilirannya memungkinkan timbulnya kehendak mengupayakan translasi kultural. Penulis Mohamad Ambri, misalnya, mengadaptasi drama Moliere, Le Medicin Malgre Lui, ke dalam bahasa Sunda dan melahirkan sebuah novel berjudul Si Kabayan jadi Dukun (1933). Demikian pula Bupati Bandung zaman kolonial, R.A.A. Wiranatakusumah, mengadaptasi buku karya penulis Prancis dan Aljazair, Etienne Dinet dan Slimane ben Ibrahim, La Vie de Mohammed: Prophete d’Allah (1918) ke dalam bahasa Belanda, Het Leven van Mohammad de Profeet van Allah (1940), dan bahasa Sunda, Riwajat Kandjeng Nabi Moehammad s.a.w. (1941).
Hari ini, ketika generasi Romain Osi berkunjung ke Bandung, interaksi antarbudaya itu kiranya tetap berlangsung.