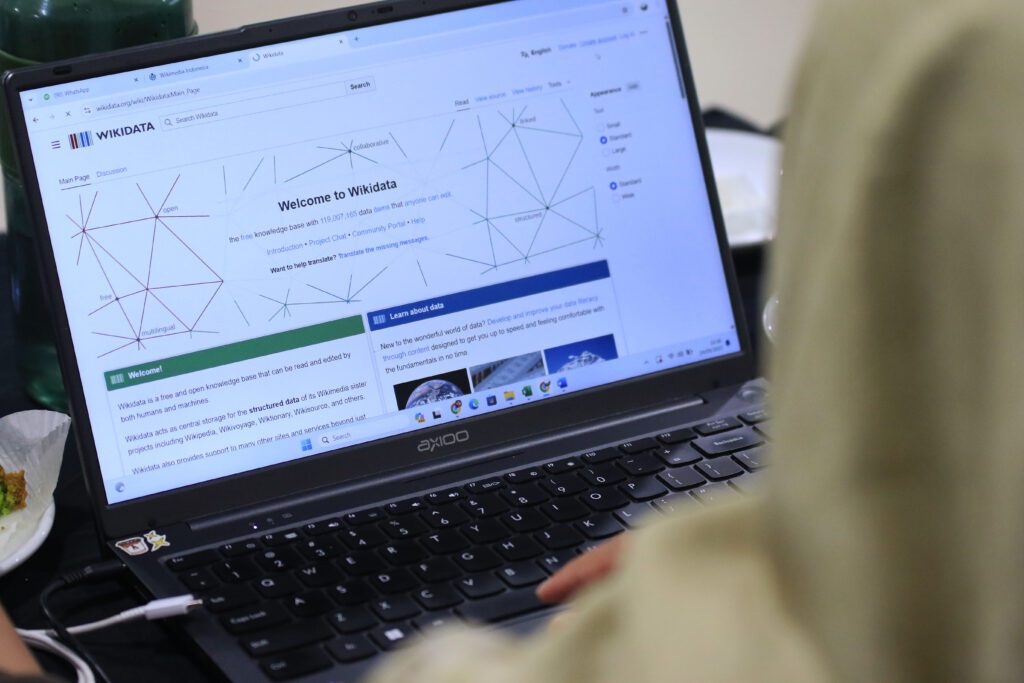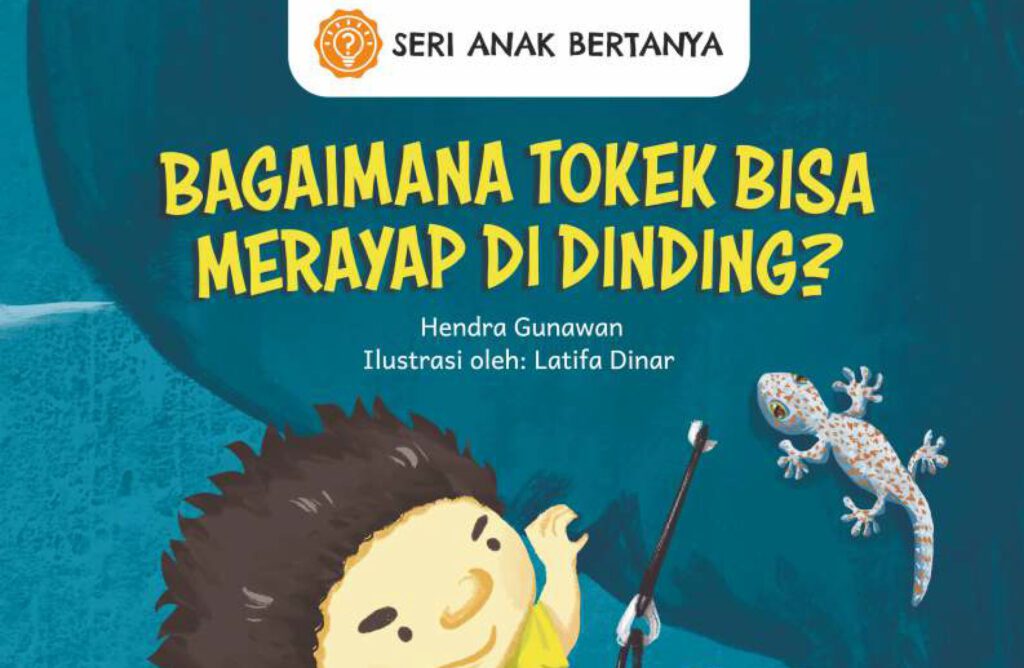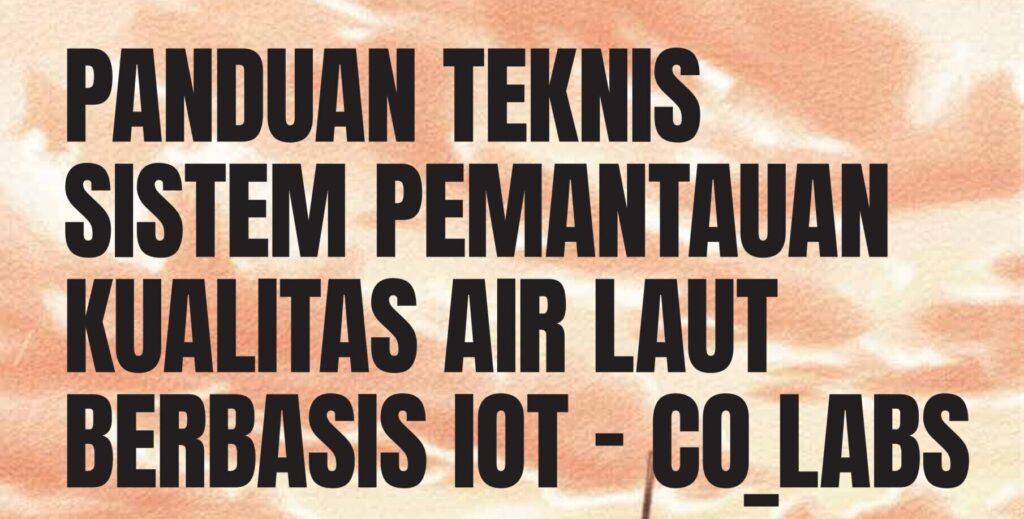Hari kedua Rural ICT Camp 2025 diwarnai dengan sesi menarik bertajuk “Presentasi Hasil Riset AI”, hasil kolaborasi antara Wikimedia Foundation dan Common Room Network Foundation di Ruang Edelweis, Wisma Hijau, Depok pada Rabu (24/9/2025). Hadir sebagai narasumber utama yaitu Lead Public Policy Specialist on Asia for Wikimedia Foundation, Rachel Judhistari yang dipandu oleh Penasihat AI Fair Forward GIZ Indonesia, Karlina Octaviany. Sesi ini membahas strategi Wikimedia dalam menggunakan kecerdasan buatan (AI) secara etis dan transparan, serta peran manusia sebagai kurator utama pengetahuan di dunia digital.
Sebelumnya Karlina Octaviany menjelaskan alasan kolaborasi ini yaitu untuk memperkenalkan sisi lain dari AI—bahwa teknologi ini tidak selalu menakutkan, tetapi bisa menjadi alat bantu yang bermanfaat bila dikelola dengan tanggung jawab dan nilai kemanusiaan.

“Kami ingin peserta mengenal ekosistem Wikipedia dan memahami bagaimana AI bekerja di baliknya—terutama soal transparansi, etika, dan panduan penggunaannya,” ujar Karlina.
Sementara itu, Rachel Judhistari menjelaskan bahwa Wikimedia Foundation adalah satu-satunya platform global top 10 yang berstatus non-profit. Dengan 270 juta pengguna Wikipedia di Indonesia setiap bulan, Wikimedia terus berkomitmen menyediakan akses informasi terbuka dan netral.
“AI bukan hal baru bagi kami. Faktanya, Wikipedia sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan selama 25 tahun terakhir,” jelas Rachel.

Namun, berbeda dengan platform lain, AI di Wikimedia berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia. Konten di Wikipedia tetap dibuat, dikurasi, dan diedit oleh manusia—oleh sekitar 300.000 kontributor aktif di seluruh dunia.
Rachel menuturkan bahwa Wikimedia memanfaatkan AI untuk membantu para editor dalam tugas-tugas berulang seperti menautkan artikel, menambah gambar, atau menerjemahkan konten lintas bahasa. Namun, setiap rekomendasi dari AI harus disetujui oleh manusia.
“AI membantu, tapi keputusan akhir tetap di tangan editor. Kami percaya, kualitas informasi yang baik hanya bisa dihasilkan melalui kurasi manusia,” katanya.
Wikimedia juga berkolaborasi dengan UNESCO dan komunitas pemeriksa fakta atau fact-checkers untuk memerangi disinformasi, terutama saat Pemilu di berbagai negara. Dalam konteks global, Wikimedia bekerja sama dengan pemerintah India melalui proyek AI4Bharat, untuk mendigitalisasi bahasa-bahasa lokal dan hampir punah agar tetap hidup di era kecerdasan buatan.
“Bukan sekadar menerjemahkan otomatis, tetapi juga memberi ruang bagi nuansa lokal dan kearifan kontekstual,” tambah Rachel.

Dalam tiga tahun ke depan, Wikimedia Foundation akan mengembangkan strategi AI global dengan prinsip “AI untuk kebaikan bersama”. Strategi ini menekankan pendekatan berpusat pada manusia (human-centered approach), penggunaan open source, multibahasa, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
Rachel juga memperkenalkan konsep Model Card, yaitu semacam label informasi yang menjelaskan asal, tujuan, serta potensi bias dalam model AI.
“Model Card seperti nutrition facts pada kemasan makanan. Pengguna berhak tahu bagaimana model AI dibuat, siapa yang melatihnya, dan apa risikonya. Transparansi ini penting untuk menghormati hak pengguna,” jelas Rachel.
Sesi diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Iswahyuddin dari Sekolah Internet Komunitas (SIK) Maros menanyakan bagaimana AI bisa dimanfaatkan dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya di bidang pengelolaan data.

Rachel menjelaskan bahwa banyak model AI global masih bias terhadap konteks budaya Barat. Inilah sebabnya Wikimedia mendorong pengembangan AI yang memahami keberagaman budaya dan wajah masyarakat dunia.
“Saat kita unggah foto ke aplikasi, kadang wajah jadi diputihkan atau diubah. Itu karena modelnya dilatih dengan data dari Eropa dan Amerika. Kita perlu model AI yang juga memahami konteks budaya dan identitas lokal,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab, peserta juga menanyakan cara menjadi kontributor di platform Wikimedia. Rachel menjelaskan bahwa siapa pun dapat bergabung tanpa sertifikasi khusus, cukup membuat akun dan mengikuti pelatihan komunitas lokal.
“Prinsip kami adalah membebaskan pengetahuan. Menjadi kontributor di Wikimedia bukan soal uang, tapi kontribusi bagi kepentingan publik—semacam amal jariyah digital,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keberagaman dalam komunitas kontributor. Selama ini, sebagian besar editor masih berasal dari Eropa dan laki-laki, sehingga Wikimedia kini aktif mengajak perempuan dan masyarakat adat untuk ikut memperkaya perspektif dan narasi di dunia digital.
Sesi ditutup dengan refleksi bersama bahwa masa depan AI seharusnya tidak hanya berfokus pada kecepatan dan efisiensi, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan transparansi. “AI harus membantu manusia berpikir kritis, bukan menggantikannya,” tegas Rachel.
“Dengan semangat berbagi pengetahuan terbuka, AI menjadi pengingat bahwa teknologi hanyalah alat dan di tangan komunitas yang kritis, kolaboratif, serta beretika, AI dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat akses informasi, inklusivitas, dan keberagaman pengetahuan di era digital,” pungkasnya***