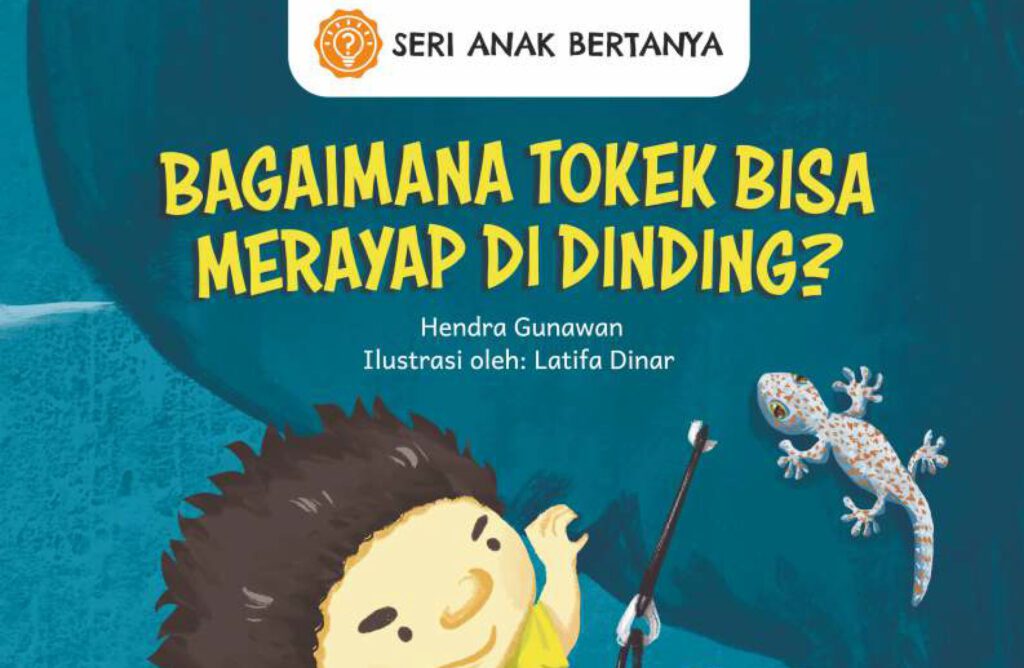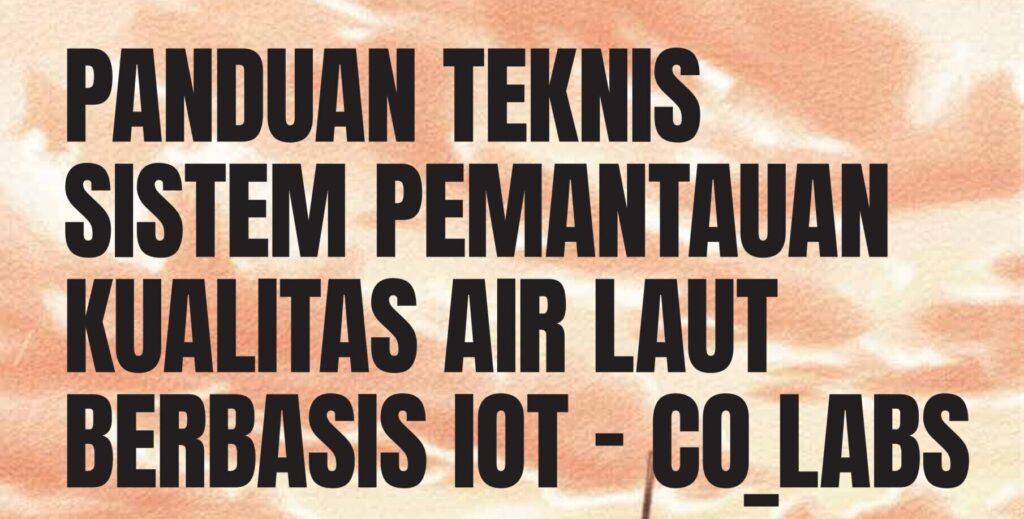Di tengah gempuran teknologi, masih banyak desa di Indonesia yang belum merasakan internet cepat dan terjangkau. Namun, ada kabar baik: di berbagai pelosok negeri, warga sendiri mulai membangun jaringan internetnya. Bukan perusahaan raksasa, tapi gotong royong komunitas. Cerita ini disampaikan oleh Project Officer Common Room, Andriani Kesa Alivia pada gelaran Lokakarya Community-centered Connectivity Initiatives (CCCI) tentang Kebijakan, Layanan Lokal Berperspektif Gender, dan Kewirausahaan Sosial oleh Common Room pada Rabu (6/8) di hadapan 11 perwakilan dari 11 jaringan Sekolah Internet Komunitas (SIK) di 10 provinsi di Indonesia.
Inisiatif seperti Community Connectivity Collaborative Initiatives (CCCI) membuktikan bahwa internet bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal sosial. Prosesnya mirip perjalanan panjang: mulai dari survei lokasi, membuat prototipe, pelatihan teknisi lokal, sampai mengatur kerja sama dengan pihak luar. “Temuan di lapangan, kadang jalannya mulus, kadang harus putar arah karena kendala sumber daya manusia (SDM), kebijakan, atau pembiayaan,” papar Kesa dalam materinya.

Saat ini ada 11 jaringan komunitas di seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh Besar, Sukabumi, Sanggau, Sulawesi sampai Bali, lalu Lombok Utara, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Taliabu di Maluku Utara. “Setiap tempat punya caranya sendiri dalam mengelola internet: Di Pulo Aceh warga menjual voucher internet Rp12 ribu per GB dan menyisihkan dana untuk perawatan. Di Ciptagelar, Sukabumi, internet dikelola komunitas adat. Tarifnya Rp10 ribu untuk pemakaian 24 jam tanpa batas, dan hasilnya bisa menabung sampai ratusan juta untuk reinvestasi. Sementara di Sanggau, harga voucher bisa Rp3.000–Rp50.000, menyesuaikan kebutuhan warga,” tutur Kesa.
Peserta SIK Ciptagelar, Revasaya mengungkapkan, “Di Ciptagelar, internet dipakai untuk menjaga budaya adat, ada siaran komunitas, pelatihan digital, bahkan dukungan dari kampus dan lembaga budaya,” tuturnya. Cerita lain datang dari peserta SIK Ciracap, Aji Kusmayadi, “Jaringan internet membantu pelajar, petani, UMKM, dan layanan publik. Model bisnisnya beragam—mulai dari koperasi sampai Social Enterprise dengan penjualan voucher, paket tematik, hingga bagi hasil dengan warung sebagai reseller lokal,” ungkap Aji.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kesa yang kerap membawa cerita baru dari lokasi yang ia datangi dalam pengembangan jaringan internet komunitas ini. “Warga desa bisa belajar, pemuda lokal jadi teknisi, belajar mengelola bisnis, dan punya keterampilan baru. Kesenjangan akses digital berkurang, terutama di wilayah terpencil. Paling penting budaya lokal tetap lestari karena bisa dipromosikan lewat platform digital komunitas,” tambah Kesa.

Bagi Kesa dan para penggerak internet komunitas ini setidaknya terdapat tiga hal utama yang membuat jaringan komunitas berhasil. “Kepemilikan lokal, pengelolaan berbasis sumber daya manusia desa, dan pembiayaan jangka panjang. Ditambah tata kelola yang transparan, dukungan kebijakan publik, dan strategi yang sesuai daya beli warga, jaringan ini bukan hanya bertahan—tapi bisa jadi motor pemerataan akses digital di Indonesia,” pungkas Kesa menutup sesi presentasinya.***