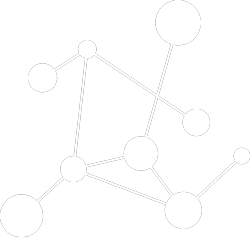Sabtu, 4 Agustus 2007, Khazanah––Lembaran Khusus Budaya di koran Pikiran Rakyat (PR) memuat sajak-sajak Saeful Badar. Senin, 6 Agustus 2007, di halaman depan PR, tepat di sebelah foto besar aksi penjaga gawang Manchester United, ditayangkan kolom kecil “Permohonan Maaf”. Redaksi PR meminta maaf atas pemuatan sajak berjudul “Malaikat” pada Khazanah 4 Agustus 2007. Dikatakan PW Muslimat NU Jabar dan “sejumlah ormas Islam” telah memprotes sajak tersebut karena dianggap menghujat akidah Islam. Redaksi PR dalam pernyataan itu mencabut sajak tersebut dan menganggapnya tidak pernah ada.
Saya sudah beberapa tahun malas membaca sajak. Saya pun tidak membaca rubrik sajak di Khazanah 4 Agustus lalu. Justru pernyataan pencabutan sajak itulah yang membuat saya membaca dan berusaha menyimak baik-baik sajak-sajak Saeful Badar.
Jumat 10 Agustus 2007 sekitar jam 9 pagi saya terima pesan pendek dari Rahim (redaktur Khazanah), “Heru, saya sudah tidak di Khazanah lagi, penggantinya belum ditetapkan, terima kasih atas kerjasamanya selama ini”. Sejak mulai disiarkan sekitar tahun 2000an, tulisan saya memang paling banyak dimuat di Khazanah, termasuk pada masa Rahim menjadi redaktur. Pagi itu saya tidak mencium persoalannya. Sore harinya, saat menghadiri diskusi Kekerasan (di) Media Massa di Pusat Kebudayaan Perancis (CCF) Bandung, dan bertemu beberapa kolega penulis, baru saya mulai menghubungkan pesan Rahim dengan pemuatan sajak Malaikat. Hikmat Gumelar dari Institut Nalar (penyelenggara diskusi) menutup pembicaraannya pada pembuka forum diskusi dengan mendeklamasikan sajak Malaikat.
MALAIKAT
Mentang-mentang punya sayap
Malaikat begitu nyinyir dan cerewet
Ia berlagak sebagai makhluk baik
Tapi juga galak dan usil
Ia meniup-niupkan wahyu
Dan maut
Ke saban penjuru.
(2007)
Ada 3 sajak Saeful Badar lain disamping sajak Malaikat. 2 dijuduli “Pantai Cimanuk”. Satu lagi dimuat paling bawah dijuduli “Penyair”.
Saya punya sejumlah penafsiran atas sajak-sajak Saeful Badar. Tapi dalam surat ini saya akan langsung melompat pada soal paling prinsipil: apa sih artinya sajak itu? Apa artinya sebuah karya seni? Sepanjang pengalaman saya, orang sering sekali mengkonfirmasikan pertanyaan ini pada seniman. Jika bisa berbincang langsung dengan seniman, kelihatannya kesempatan ini amat baik untuk menyoal “arti” karya. “Mas/Mbak, apa sih maksudnya bikin karya seperti itu?”. Bagi saya pribadi pertanyaan kepada seniman ini, sekalipun bisa dianggap informasi dari tangan pertama, tetap tidak bisa dijadikan faktor paling determinan untuk memaknai karya seni.
Ketika karya telah disiarkan, baik pengarang maupun pembaca punya kedudukan setara dalam praktek pemaknaan. Si pengarang dipengaruhi berbagai faktor dalam merumuskan ide dan mewujudkan karya, demikian pula pembaca dalam memirsa karya. Siapakah yang paling berhak memaknai karya seni? Tidak ada. Persis di sini indahnya dunia seni, yaitu suatu alur diskursif. Makna merupakan hasil negosiasi, melalui proses diskusi. Semua orang setara.
Pernyataan bahwa sajak Malaikat menghujat akidah Islam merupakan kesimpulan dari proses memaknai karya dari sebagian pihak. Kesimpulan mengenai makna sebuah karya seni tidak bisa dipaksakan kepada khalayak. Sebagian pihak tidak bisa memaksakan pemahamannya atas sesuatu kepada pihak lain. Pemaksaan semacam ini hanya terjadi di bawah rejim otoriter. Dan kita banyak belajar bahwa di bawah rejim otoriter seni justru sering muncul sebagai oase dari apa yang biasa dikumandangkan sebagai “kebebasan berpendapat”. Kenapa? Sederhana saja, karena prinsip kesetaraan dalam memaknai karya seni.
Saya tidak tahu apakah redaksi PR sebelum mencabut sajak Malaikat berdiskusi terlebih dahulu dengan Saeful Badar. Saya juga tidak tahu apakah memang benar Rahim dicabut kewenangannya sebagai redaktur Khazanah karena memuat sajak Malaikat. Dan kalau ya, saya juga tidak tahu apakah Rahim diajak berdiskusi sebelum pihak redaksi mengambil keputusan. Yang penting adalah, pihak redaksi PR tidak bisa “mencabut” sajak yang telah disiarkan. Ini kan mustahil; bagaimana bisa suatu teks tertulis yang telah dicetak banyak-banyak dan disebarkan kemudian dianggap tidak ada?
Redaksi PR mencabut sajak dengan alasan bahwa ada protes dari sementara pihak. Artinya redaksi PR mengakui bahwa bukan dirinya sendiri yang berkepentingan dengan ruang di PR. Walaupun pihak redaksi adalah pengelola media massa, tetap saja ruang tersebut merupakan ruang publik, artinya banyak yang berkepentingan. Dan makin kentara ke-publik-an di ruang itu makin bagus kualitasnya.
Terakhir, hari ini Senin 13 Agustus 2007 sekitar jam 4 sore, Aminudin TH. Siregar, seorang kolega kurator, mengirim pesan pendek, “sebaiknya penulis-penulis mogok nulis di Khazanah, kalau memang Rahim dicopot karena memuat sajak, jelas enggak fair…saya pribadi bersedia mogok nulis di PR”. Saya sampai sekarang masih ragu apakah boikot merupakan tindakan yang paling efektif. Tapi sesuatu memang harus dilakukan, sebab, sungguh merupakan hal yang sangat tidak wajar jika redaksi PR mengambil keputusan dengan hanya memperhatikan satu warna pendapat dari sebagian pihak. Sungguh merupakan ketidak-adilan jika redaksi PR mencabut sajak dan mencabut kewenangan Rahim tanpa melalui diskusi.
Bandung, 13 Agustus 2007
Heru Hikayat
Kurator seni rupa, tinggal di Bandung